ULAMA, BUYA,USTADZ, DA’I atau MUBALLIGH
ISLAM, setahu
saya, bukan saja universal sifatnya, tetapi juga populis, merakyat. Hubungan
antara da‟i/muballigh dengan ummat adalah horizontal, egaliter, dan setara. Dan
da‟i atau muballigh itu adalah bahagian yang tak terpisahkan dari ummat.
Dia ada di tengah-tengah ummat, dan bersama ummat. Sistem papacy atau
kependetaan seperti dalam agama Nasrani yang pendeta atau pastornya memainkan
peran sebagai zending atau missionaris itu diangkat (ordained),
bersertifikat, pakai pakaian seragam, apa lagi bergaji, berlaku untuk mereka
tetapi tidak dikenal dalam Islam, dan tidak perlu. Itu bedanya. Jika sekarang
ada dari antara ulama sendiri yang mau menjadikan da‟i dan muballigh itu seperti cara di gereja itu, patut dipertanyakan: Aina
mafarr.
Yang dijaga
adalah kedekatan, bukan jarak. Makin dekat dengan rakyat, makin disukai, dan
makin lekat kasih-sayang itu. Da‟i dan muballigh
adalah bahagian dari rakyat dan hidup bersama rakyat atau ummat itu sendiri.
Dan setiap
muslim, laki-laki dan perempuan, pada dasarnya adalah da‟i dan muballigh. Sekurang-kurangnya untuk diri dan keluarganya.
Apatah lagi kalau juga bisa untuk orang lain. Ucapan Rasul: “Sampaikan olehmu
walau satu ayat,” maksudnya adalah itu.
Namun, perlu pula
sejumlah dari antara ummat yang menjadikan dakwah dan tabligh menjadi bahagian
dari profesi atau panggilan hidupnya. Al Qur`an: “Hendaklah sebahagian dari
kamu menjadi kelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat baik
dan melarang perbuatan mungkar,” ke sana perginya.
Mereka tidak
harus hanya itu kerjanya, seperti para pastor dan pendeta itu. Para da‟i dan muballigh yang professional bisa sebagai apa saja. Bisa
pejabat, bisa tentara, bisa teknokrat, bisa pedagang, bisa petani, bisa guru,
bisa ibu rumah tangga, apapun. Yang penting, mereka menyediakan sebagian
ataupun sebagain besar dari waktunya, untuk berdakwah dan bertabligh. Dan jika
dia dari keluarga mampu, cukup yang akan dimakannya dan cukup pula untuk
pembiayai anak-isterinya, silahkan pula kalau seluruh waktunya dipakainya untuk
berdakwah dan bertabligh itu.
Soalnya karena
tidak setiap muslim ataupun muslimat punya bakat untuk menjadi da‟i/muballigh secara professional. Selain bakat, talen, juga perlu
kemampuan berpidato, berbicara fasih di muka umum, beretorika, dsb, dengan
suara dan gaya yang menarik dan menyenangkan. Walau semua itu bisa dipelajari,
tetapi tidak semua orang bisa. Makanya muncullah barisan da‟i dan muballigh, yang karena ilmu agamanya yang mendalam biasanya
mereka juga adalah ulama, atau sekurangnya ustaz/ustazah. Bertambah seorang da‟i/muballigh menguasai ilmu agama dan ilmu lain-lainnya juga, pandai
dia membawakannya, dan pandai pula dia membawakan diri, maka bertambah senang
orang padanya. Apalagi kalau di atas semua itu akhlaknya baik dan teruji,
sehingga dia menjadi orang panutan, menjadi uswatun hasanah, dan
pemimpin.
Dengan dia
menjadikan dirinya da‟i, muballigh, atau ulama sendiri, tidaklah dia lalu menjadikan
dirinya berbeda dari ummat lainnya. Da‟i /muballigh yang berhasil
adalah da‟i atau muballigh yang tidak
memperlihatkan bedanya dengan ummatnya. Justru yang dicarinya adalah
kedekatannya dan selalu berada di tengah-tengah ummat itu; bukan di atas atau
diluarnya. Da‟i/muballigh ataupun ulama
yang mencari-cari tuah diri dengan membikin pakaiannya berbeda dari ummatnya,
dengan jubahnyakah, serbannyakah, kain berlipat yang disandang di bahunya kah, jenggotnyakah, atau apapun yang membikin dia berbeda dari yang lainnya,
itu tanda bahwa dia minta dihargai, dilebihkan dari yang lainnya, dan
diistimewakan. Apalagi kalau sudah sampai pula kepada usaha untuk menjadikan
dirinya jadi Tuanku, jadi Kiyai, jadi Wali, jadi apapun yang menyebabkan dia diistimewakan,
berbeda dari yang lainnya. Tangannya ingin dicium, sisa airnya diminum, sisa
makanannya dimakan dan diperebutkan.
Bagi saya susah
untuk memahami ada orang yang sengaja memanggil dirinya Kiyai, Ustadz, Buya,Tuanku,
apalagi Wali. Karena merasa diri Kiyai, Tuanku atau Wali, ada saja itu yang
merasa kewajiban syariat tidak lagi wajib bagi mereka, karena secara tasawuf
dia merasa sudah sampai ke tingkat makrifat. Karena hijab telah terbuka, dan
dirinya dekat dengan Tuhan, atau bahagian dari Tuhan itu sendiri, dalihnya.
Pada hal da‟i/muballigh/ulama yang sebenar da‟i/muballigh/
ulama adalah yang membuat dirinya tidak berbeda dari yang lainnya, sehingga tidak
ada masalah komunikasi dan jarak sosial itu. Dia tentu saja diharapkan lebih
saleh, lebih tawadhuk, dan lebih memahami segi-segi dan sisi-sisi dari agama.
Kalau bisa malah punya otoritas, artinya menguasai, dalam hal ilmu agama,
sehingga dia menjadi orang tempat bertanya dalam hal yang berkaitan dengan
masalah agama. Seorang da‟i, muballigh, apalagi ulama, di samping memiliki otoritas, tentu
saja, lebih lagi, memiliki integritas, martabat diri. Dengan itu dia
memperlihatkan kelebihannya, dan bukan dengan atribut, nama, pangkat, pakaian
dan ciri-ciri penampilannya itu.
Bahwa pemerintah
atau masyarakat sendiri memberi nafkah kepada mereka karena profesinya itu,
boleh-boleh saja. Tetapi tidaklah dengan menempatkan mereka sebagai orang yang
digaji, sebagaimana pegawai negeri, karena profesinya itu. Kecuali kalau dia
adalah juga qadhi, garin, malim, muazzin, penjaga mesjid, yang tugasnya adalah
memelihara mesjid dengan segala kegiatan rutinnya itu sehingga tidak ada waktu
baginya untuk mengerjakan pekerjaan yang lain untuk mencari nafkah.
Seperti dengan
anggota ummat lain-lainnya, merekapun harus memikirkan dan berusaha untuk
mendapatkan nafkah dengan usaha apapun yang diredai, dan tidak mengandalkan
hanya kepada pemberian dari pemerintah atau masyarakat itu.
Bahwa da‟i/muballigh, seperti juga ulama, membentuk organisasi professi
sendiri, sah-sah saja. Dan siapa pula yang akan melarang. Apalagi kalau
tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan mutu dari kinerjanya.
Bahwa da‟i tekanannya adalah di bidang dakwah bil hal, dan muballigh di
bidang dakwah bil lisan, juga sah-sah saja. Dalam praktek ummat dan
masyarakat tak terlalu membedakannya. Kata da‟i itu
sendiri dalam konteks sosiologi agama di Indonesia dikenal baru kemudian,
sementara sebelumnya yang dikenal adalah muballigh yang kerjanya bertabligh. Siapa
bilang kalau da‟i hanya melakukan dakwah bil hal, dan bil lisan tidak.
Da‟i yang melakukan dakwah bil hal dalam masyarakat Indonesia
sekarang ini LSM namanya, bukan da‟i. Sebagai LSM
diapun dapat duit, entah dari mana sumbernya. Karenanya istilah da‟i dan muballigh, dakwah dan tabligh, biasa diperganduhkan. Maksudnya
itu juga. Dan muballigh pun, seperti da‟i juga, biasa
tidak hanya sekedar menyampaikan tetapi juga menuntun dan melakukan tugas-tugas
keagamaan yang sifatnya bil hal atau amal sosial itu.
Yang menjadi
masalah dengan da‟i, muballigh, dan bahkan ulama sendiri, di tengah-tengah masyarakat
ummat sekarang ini, adalah karena kebanyakan pandainya cuma menyampaikan,
tetapi tidak memberi contoh dan tauladan. Bahkan tidak jarang, tak bersua yang
dikatakannya itu dengan yang dikerjakannya. Atau bahkan sebaliknya,
bertentangan.
Lunturnya muruah
para da‟i/mubaligh/ulama di mata ummat, sebagaimana lunturnya muruah para
umara` dan zuama` di mata rakyat, adalah karena tidak nyambungnya, atau
tidak satunya, kata dan perbuatan itu. Mereka tidak menempatkan diri sebagai
suri tauladan, sebagai contoh panutan bagi ummat dan rakyat.
Masalahnya
“hanya” itu. Tetapi karena “hanya” itu pulalah menjadi rusak semua-semua. Dan
masyarakat kita, baik ummat maupun rakyat, kehilangan tempat bergantung,
karenanya juga kehilangan dan ketiadaan pemimpin. Yang jadi pejabat banyak,
jadi ulama banyak, jadi da‟i dan muballigh banyak,
tetapi yang jadi pemimpin langka atau bahkan nyaris tidak kelihatan.
Dilema Indonesia
dan masyarakat Islam di Indonesia khususnya sekarang ini adalah karena
ketiadaan pemimpin dan kepemimpinan dengan suri tauladan yang baik itu. Artinya
umara`, zu‟ama`, „ulama`, termasuk da‟i dan muballigh,
yang juga menempatkan dirinya sebagai pemimpin ummat dan rakyat itu. Sebuah anugerah
dan petunjuk (hudan) dari ALLAH insya ALLAH, bagaimanapun, pasti akan
terjadi di tengah-tengah masyarakat ummat dan rakyat Indonesia ini manakala
para umara`, dan ulama` beserta da‟i dan
muballighnya jikakembali menempatkan diri sebagai pemimpin ummat dan rakyat
yang suri tauladan itu dimulainya dari dirinya sendiri, dan mereka bimbing
rakyat dan ummat ini ke jalan yang benar dan diredhai-Nya. ***
MN








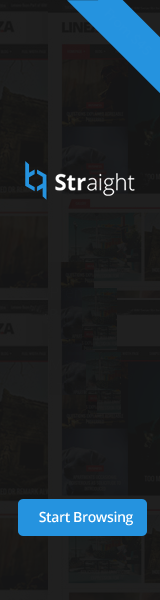


































No comments:
Post a Comment