PADA 27 Desember 2017 lalu, saya mendapat undangan
dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, untuk menjadi
pembicara dalam sebuah Seminar Nasional tentang Keislaman dan
Kebangsaan. Pembicara lainnya yang diundang hadir adalah Prof. Dr.
Mahfud MD dan Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo, guru besar Ilmu Hukum
Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, serta Danrem Yogyakarta.
Dalam seminar itulah, saya pertama kali mengenal sosok Prof. Sudjito,
yang dikenal juga sebagai pakar tentang Pancasila. Prof. Sudjito
memaparkan uraiannya tentang Pancasila dengan judul: “Memposisikan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu”.
Beliau tampil pada sesi pertama bersama wakil dari Korem Yogyakarta.
Sedangkan saya dijadwal tampil pada sesi berikutnya bersama Prof. Mahfud
MD.
Tema itu menarik. Karena itu, saya dengan tekun menyimaknya. Sejumlah
poin penting yang disampaikan Prof. Sudjito diantaranya adalah bahwa:
(a) Ilmu adalah lentera kehidupan (b) Ilmu sebagai institusi pencarian
kebenaran, dinamis, terus berkembang, dan (c) ilmu bersifat amaliah,
yakni berdwitunggal dengan amal.
Prof. Sudjito menggariskan bahwa epistemologi keilmuan yang
berparadigma Pancasila adalah yang mengakui bahwa asal-usul dan hakikat
ilmu adalah dari Tuhan, berproses dalam kehidupan manusia, bermuara pada
pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, karakteristik ilmu
yang berparadigma Pancasila adalah: (a) bersifat teistik, obyektif, dan
universal (sila 1), (b) bersifat humanistik, naturalistik (sila 2),
(c) Metode keilmuan holistik (sila 3), (d) Kebenaran diperoleh melalui
konstruksi sosial-religius, musyawarah-mufakat (sila 4), dan (e)
Keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (sila 5).
Lebih jauh Prof. Sudjito mengingatkan, bahwa saat ini Pendidikan Ilmu
di Perguruan Tinggi masih menghadapi permasalahan dan tantangan antara
lain: (a) Kurikulum masih berkarakter liberalistik, individualistik, dan
sekuler (b) adanya pengaruh narkoba dan ideologi ekstrim di kampus yang
perlu ditanggulangi (c) pengaruh model-model pendidikan Barat yang
berkarakter rasionalistik semata, tetapi nihil moralitas kemanusiaan,
dan (d) belum semua dosen ber-Pancasila.
Terakhir, menurut Prof. Sudjito, Perguruan Tinggi diharapkan
menghasilkan lulusan yang cinta kepada Pancasila, paham hukum sebagai
order (tatanan) dan mampu mengamalkan ilmu untuk kemaslahatan umat.
Dalam pandangannya, ilmuwan professional adalah yang bermoral Pancasila,
berwawasan kebangsaan, dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Secara umum, pandangan Prof. Sudjito tentang Pancasila itu menawarkan
keserasian antara agama dan Pancasila. Sosok ilmuwan yang taqwa sebagai
cita ideal ilmuwan Indonesia mensyaratkan penerapan ajaran agama.
Setelah seminar, kami sempat berbincang singkat, dan beliau menegaskan
bahwa orang yang ber-Pancasila adalah orang yang religius.
Saya merasa ada kesepahaman dengan Prof. Sudjito dalam soal hubungan
antara Islam dengan Pancasila. Pernyataan beliau bahwa pengajaran ilmu
di Perguruan Tinggi masih berkarakter liberalistik, individualistik, dan
sekuler, perlu kita garisbawahi. Sebagai akademisi senior di sebuah
universitas besar di Indonesia, pernyataan itu menyiratkan keprihatinan
yang mendalam. Apalagi, UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah harus
menyelenggarakan pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan,
ketaqwaan, dan akhlak mulia. Ilmu-ilmu sekuler tidak akan membawa
mahasiswa menuju pada iman, taqwa, dan akhlak mulia.
Bahaya ilmu sekuler
Cendekiawan Kristen Harvey Cox dalam buku terkenalnya, The Secular City,
menjelaskan bahwa sekularisasi adalah pembebasan manusia dari asuhan
agama dan metafisika; pengalihan perhatiannya dari ‘dunia lain’ menuju
dunia kini. (Secularization is the liberation of man from religious
and metaphysical tutelage, the turning of his attention away from other
worlds and towards this one).
Buku Harvey Cox diawali dengan bab “The Biblical Source of Secularization”. Ia mengutip pendapat teolog Jerman Friedrich Gogarten: “Secularization is the legitimate consequence of the impact of biblical faith on history.” Bahwa sekularisasi adalah akibat logis dari dampak kepercayaan Bible terhadap sejarah.
Dalam bukunya, Christianity in World History, Arend Theodor van Leeuwen, mencatat, bahwa penyebaran Kristen di Eropa membawa pesan sekularisasi. Kata Leeuwen, “Christianization and secularization are involved together in a dialectical relation.”
Maka, menurutnya, persentuhan antara kultur sekular Barat dengan kultur
tradisional religius di Timur Tengah dan Asia, adalah bermulanya babak
baru dalam sejarah sekularisasi. Sebab, kultur sekular adalah hadiah
Kristen kepada dunia.(Christianity’s gift to the world). (Pendapat Leeuwen dikutip dari buku Mark Juergensmeyer, The New Cold War?, (London: University of California Press, 1993
Salah satu ilmuwan muslim terkemuka yang gigih menolak gagasan
sekulerisasi adalah Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas. Buku karya
al-Attas, Islam and Secularism, yang terbit awal 1970-an, sudah
diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Al-Attas menolak klaim
Harvey Cox bahwa akar sekularisasi terdapat dalam kepercayaan Bible.
Bagi al-Attas, akar sekularisasi bukan terdapat dalam Bible, tetapi
terdapat dalam penafsiran orang Barat terhadap Bible.
Sekularisasi bukanlah dihasilkan oleh Bible, namun ia dihasilkan oleh
konflik lama antara akal dan Bible di dalam pandangan hidup orang
Barat. Kata al-Attas: “The claim that secularization has its roots
in biblical faith and that it is the fruit of the Gospel has no
substance in historical fact. Secularization has its roots not in
biblical faith, but in the interpretation of biblical faith by Western
man…”.
Dalam pandangan al-Attas, worldview orang Barat telah menempatkan Tuhan menjadi manusia dan manusia dijadikan Tuhan (deity is humanized and man is deified).
Manusia telah menempatkan dirinya sebagai Tuhan yang merasa berhak
mengatur diri dan seluruh alam sesuai kemauannya sendiri. Manusia
seperti itu sejatinya telah hilang adab kepada Tuhan. Semua itu berawal
dari ilmi yang salah. Ilmu yang sangat merusak kehidupan manusia.
Peringatan akan bahaya ilmu sekuler ini juga pernah disampaikan oleh
pakar filsafat sains, Seyyed Hossein Nasr. Menurutnya, kini makin banyak
manusia yang sadar akan bahaya penerapan sains Barat yang menyebabkan
kehancuran lingkungan hidup dan mengarah pada lumpuhnya tatanan alam
ini. Kata Nasr: “To day more and more people are becoming aware that
the applications of modern science, a science witch until a few decades
ago was completely Western and which has now spread to other
continents, have caused directly or indirectly unprecedented
environmental disasters, bringing about the real possibility of the
total collapse of the natural order.” (Seyyed Hossein Nasr, The Need for a Sacred Science, (New York: State University of New York Press, 1993).
Di Indonesia, bahaya ilmu sekuler pun sudah disampaikan oleh banyak
ilmuwan muslim. Mohammad Natsir, misalnya, dalam pidatonya di Majelis
Konstituante, tahun 1957 sudah mengingatkan, bahwa manusia Indonesia
hanya punya dua pilihan: (1) memilih faham sekulerisme (la-dieniyah) tanpa agama, atau (2) memilih faham agama (dieny).
Dan inilah penjelasan Mohammad Natsir, pahlawan nasional yang juga
pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), tentang sekulerisme:
“Sekulerisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham tujuan dan sikap hanya di dalam batas hidup keduniaan. Segala sesuatu dalam kehidupan kaum sekuleris tidak ditujukan kepada apa yang melebihi batas keduniaan. Ia tidak mengenal akhirat, Tuhan, dsb. Walaupun ada kalanya mereka mengakui akan adanya Tuhan, tapi dalam penghidupan perseorangan sehari-hari umpamanya, seorang sekuleris tidak menganggap perlu adanya hubungan jiwa dengan Tuhan, baik dalam sikap, tingkah laku dan tindakan sehari-hari, maupun hubungan jiwa dalam arti doa dan ibadah. Seorang sekuleris tidak mengakui adanya wahyu sebagai salah satu sumber kepercayaan dan pengetahuan. Ia menganggap bahwa kepercayaan dan nilai-nilai moral itu ditimbulkan oleh masyarakat semata-mata. Ia memandang bahwa nilai-nilai itu ditimbulkan oleh sejarah atau pun oleh bekas-bekas kehewanan manusia semata-mata, dan dipusatkan kepada kebahagiaan manusia dalam penghidupan saat ini belaka…”
Menurut Natsir, bagi ilmuwan sekuler, “Ilmu pengetahuan sudah dijadikan tujuan tersendiri, science for the sake of science.” Pandangan sekuler, kata Natsir, sangat berbahaya, karena “menurunkan sumber-sumber nilai hidup manusia dari taraf ke-Tuhanan kepada taraf kemasyarakatan semata-mata.”
Natsir memberi contoh. Misalnya, ajaran tidak boleh
membunuh, kasih sayang sesama manusia, semuanya itu menurut sekulerisme,
sumbernya bukan wahyu Ilahi, akan tetapi apa yang dinamakan:
penghidupan masyarakat semata-mata. Jika dulunya, karena nenek moyang
kita menganggap bahwa hidup damai dan tolong menolong akan menguntungkan
semua pihak, maka timbullah larangan untuk membunuh dan bermusuhan.
Jadi, tujuannya adalah ‘perdamaian’.
Natsir memandang, bahwa pandangan semacam itu telah menurunkan
nulai-nilai adab dan kepercayaan ke taraf perbuatan manusia dalam
pergolakan masyarakat. Dengan begitu, maka pandangan manusia terhadap
nilai-nilai tersebut merosot. Manusia merasa dirinya lebih tinggi
daripada nilai-nilai itu sendiri! Manusia menganggap bahwa nilai-nilai
itu bukan sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi, tapi sebagai “alat
semata-mata”, karena semua itu adalah ciptaan manusia sendiri.”
Kritik Mohammad Natsir terhadap sekulerisme itu sangat tajam. Karena
itulah, Natsir berjuang sepanjang hidup untuk melawan sekulerisme
melalui berbagai bidang kehidupan, khususnya bidang politik dan
pendidikan. Untuk itu, Natsir tercatat aktif dalam proses pendirian
sejumlah universitas Islam di Indonesia.
Kini, dengan adanya kritik Prof. Dr. Sudjito terhadap pengajaran
ilmu-ilmu sekuler di Perguruan Tinggi, semoga semakin banyak yang sadar
akan bahaya ilmu-ilmu sekuler tersebut. Tentu tidak salah jika kita
berharap, semoga kampus UGM menjadi salah satu pelopor dalam gerakan
“de-sekulerisasi ilmu”, sebagai pijakan menuju pembentukan
ilmuwan-ilmuwan yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia (UUD 1945,
pasal 31 (c)).*/ Depok, 27 Februari 2018
Penulis adalah Ketua Program Magister dan Doktor Pendidikan
Islam—Universitas Ibn Khaldun Bogor. Catatan Akhir Pekan (CAP) hasil
kerjasama Radio Dakta 107 FM
posted by @Dd








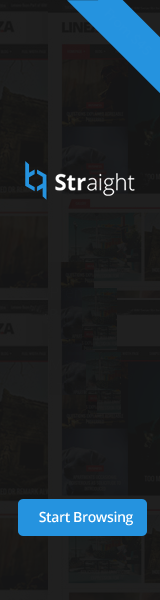





























No comments:
Post a Comment