Seorang teman datang pada saya dan bertanya apa arti kebahagiaan itu. Entah mengapa, meski pertanyaannnya sangat mudah, tapi saya tidak bisa langsung begitu saja memberinya jawaban. Selama dua bulan, saya hanya tersenyum dan meminta dia bersabar dan memberi saya waktu yang cukup untuk menguraikan jawabannya. Rentang waktu itu kini sudah berlalu dua bulan lamanya. Setiap kali bertemu dengannya, dia selalu bertanya apa jawabannya.
“Apa mas arti bahagia itu? Seperti apa rasanya? Bagaimana bentuknya?”
“Bahagia itu tidak bisa dijabarkan begitu saja dengan kata-kata. Bahagia itu hanya bisa dirasakan di hati dan hanya orang itu sendiri yang bisa merasakannya.” Saya mencoba memberi jawaban padanya. Tapi rupanya jawaban saya tidak cukup membuatnya puas.
“Itu jawaban yang sangat klise. Saya ingin tahu lebih banyak lagi, tunjukkan pada saya secara lebih jelas apa itu bahagia. Saya sangat membutuhkan jawabannya, karena saya ingin bisa selalu merasa bahagia.”
Sampai disitu saya kembali terdiam. Bukan karena tidak tahu apa yang ingin saya katakan. Jika saja saya langsung berbicara padanya panjang lebar tentang arti bahagia saat itu juga karena dia sangat menginginkan jawabannya segera; yang saya pikirkan adalah, apakah jawaban instan saya akan bisa memuaskan rasa ingin tahunya yang mendesak itu? Akhirnya, saya mengambil keputusan untuk menunda (kembali) sejenak jawaban yang ingin saya berikan padanya dan memintanya untuk bersabar agar saya bisa menjelaskan padanya secara lebih jelas apa arti bahagia itu.
“Beri saya tambahan waktu untuk mencari penjelasan yang gamplang pada kamu apa itu bahagia. Kamu sabar yah menunggu.”
Hmm. Ngomong-ngomong soal arti bahagia.
Ada sebuah kejadian yang cukup berkesan dihati saya berkenaan dengan perasaan bahagia. Kejadiannya sangat sederhana dan mungkin ada beberapa di antara kalian yang pernah mengalaminya juga. Wallahua’lam.
Kejadiannya bermula di suatu hari ketika saya dalam perjalanan menuju ke pasar. Di pinggir jalan beraspal saya bertemu dengan seorang bapak tua penjual bangku. Matahari sangat terik sehingga cuaca sangat terasa membakar kulit dan mengeringkan kerongkongan. Pepohonan yang berjajar di pinggir jalan pun rasanya tidak mampu lagi memberikan kesejukan lewat kerindangannya. Dalam suasana seperti itulah saya bertemu dengan bapak tua penjual bangku. Usianya mungkin sekitar 65-an tahun atau lebih. Kulit tubuhnya yang gosong terbakar matahari sudah banyak yang keriput. Kaki dan tangannya kurus sehingga terlihat seperti kulit yang membalut tulang saja. Matanya tampak masuk ke dalam pertanda dia sangat kurang waktu tidurnya. Dengan tubuh lemah dan sedikit gemetar, dia duduk di atas bangku bambu tua yang dijualnya. Napasnya terdengar mengik dan memburu diiringi batuk kering yang terdengar berat beberapa kali. Bapak tua itu terlihat sangat kepayahan dengan pekerjaan dan penyakitnya. Dengan tatapan mata kelelahan dan sisa senyum yang dipaksakan dari bibir keringnya, bapak tua itu menyapa saya dan menawarkan bangkunya.
“Nak, beli bangku bapak nak.“ Wajah tuanya sangat memelas sehingga saya tidak bisa menghiraukan begitu saja sapaannya. Saya mencoba untuk tersenyum dan secara reflek langsung melirik bangku bambu tua yang dijajakannya. Bangku bambu itu tampaknya akan sulit untuk laku. Entah sudah berapa lama dia memikulnya kesana kemari. Rasanya sudah cukup lama. Ada bekas memutih di kaki bangku bagian kanan bawah bekas tapak bapak tua yang memang memanggul bangku itu di atas pundaknya. Begitu juga di beberapa bagian lain tampak cat pelitur kayunya mulai memutih bahkan ada yang mulai terkelupas karena terbakar sinar matahari. Beberapa bagian bahkan memperlihatkan jalinan tali bambu yang menghubungkan ruas-ruas bambu mulai aus dan tampak rentan. Saya tidak yakin apakah bangku bambu itu akan bisa laku dalam waktu cepat tapi saya sendiri saat itu tidak membutuhkan bangku jadi tidak mungkin rasanya saya membelinya. Akhirnya saya tawarkan dia makanan sekedarnya untuk menghilangkan keletihannya bekerja serta menawarkan bantuan untuk berobat mengobati sakit batuk bengiknya yang terdengar sangat parah. Bapak tua itu hanya tersenyum tabah.
“Tidak nak. Bapak lebih senang jika bangku bapak laku terjual jadi bapak bisa menjual bangku yang lain. Beli saja bangku bapak.” Pedagang. Siapa yang tak hendak barang dagangannya laris. Tapi usia tua dan kondisi bapak tua itu sungguh membuat hati menjadi miris. Harga bambu yang dipikulnya kesana kemari selama beberapa hari itu hanya ditawarkan sebesar Rp 50.000. Untuk sebuah bangku bambu yang mulai memudar warnanya dan segala pertimbangan kekurangan yang dimiliki oleh bangku bambu bukan buatan pabrik, itu harga yang cukup pantas. Bahkan beberapa orang mungkin merasa itu harga yang mahal. Tapi untuk sebuah kelelahan berjalan berpuluh kilometer keluar masuk kampung, panas dihadang hujan diterjang, rasa lapar terlewati, rasa sakit tak dirasakan, itu adalah harga yang masih sangat murah. Padahal uang itulah yang akan diberikan pada istri dan cucunya untuk kehidupan selama satu bulan di kota besar Jakarta.
Pertemuan singkat itu berlalu. Malam berganti siang dan siang berganti malam. Beberapa hari kemudian saya bertemu lagi dengan bapak tua itu. Kali ini, dia masih mengangkut bangku bambu yang sama. Baju lusuhnya pun masih baju yang sama, seragam korpri tua yang sudah mulai memudar warna birunya dan tak ketinggalan kaki yang tidak pernah beralas kaki. Saya mengajak si bapak tua itu mampir ke rumah saya dan menjamunya ala kadarnya.“Bagaimana pak, sudah berobat ke dokter?” Saya bertanya iseng, karena sepanjang pertemuan beberapa saat itu si bapak hanya menunduk terdiam menikmati teh manis serta kue tanpa suara; hanya sesekali terdengar suara batuk keringnya yang khas.
“Belum nak.“ Si bapak tua tersenyum sopan malu-malu dan segera setelah senyumnya mengembang, sebuah batuk menghilangkan senyum yang terkembang itu. Saya tahu bapak tua itu belum mengobati sakitnya. Entah sejak kapan dia mulai sakit tapi rasanya bapak tua itu sendiri tidak pernah mempunyai pikiran untuk mengobati sakitnya itu.
“Kenapa pak? Nanti sakitnya kian parah. Apakah uang tempo hari itu tidak cukup untuk berobat?” Bapak itu menjawab pertanyaan saya dengan sebuah gelengan. Gelengan yang diiringi wajah yang tidak menampakkan kesusahan sama sekali (subhanallah).
“Tidak. Cukup Nak. Tapi saya sengaja tidak menggunakannya untuk berobat. Saya belikan makanan dan pakaian untuk istri dan cucu saya. Sudah lama kami makan tak berlauk. Saya juga belikan cucu saya mainan. Dia senang sekali kemarin. Mulutnya tidak berhenti bersenandung sepanjang hari. Kebahagiaan cucu saya itu, lebih daripada obat bagi bapak.”
Bapak itu bercerita dengan mata berbinar cerah. Ada semangat yang tiba-tiba menghiasi wajah tuanya yang kelelahan. Senyumnya mengembang dan matanya menerawang menembus lantai teras yang dipandanginya. Rasanya senyum dan senandung cucunya saat itu kembali terdengar dir telinganya. Dia sangat terlihat begitu bahagia. Bahkan rona kebahagiaan itu mampu menghadirkan warna semburat kemerahan di pipinya yang sangat pucat.Subhanallah. Itulah kebahagiaan. Saya kini bisa melihat apa itu kebahagiaan. Melihat senyum bahagia bapak tua itu saya ikut bahagia dan terharu. Tapi bagaimana caranya memberitahu pada teman saya itu? Apakah dengan cara merekam percakapan dan suasana yang baru saja saya alami pada teman saya itu dengan lengkap dalam bentuk film dokumenter? Bagaimana jika teman saya itu tidak bisa melihat pesan bahagia yang baru saja terkirim?
“Mbak, saya sekarang sudah menjadi orang yang tidak sabaran. Saya tidak sabar mencari jawaban apa arti bahagia. Apa yang harus saya miliki untuk bisa bahagia?” Pertanyaan terakhirnya, apa yang harus dimiliki untuk bisa bahagia. Saya yakin, ukuran bahagia itu tidak bersifat materi. Ini karena manusia secara fitrahnya, tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dia miliki. Jika dia belum memiliki sesuatu, dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Ketika suatu saat dia berhasil mendapatkannya maka nilai kenikmatan memilikinya adalah sebuah kenikmatan sesaat yang segera hilang dalam sekejap. Mengapa? Karena setelah itu ada sebuah keinginan baru, yaitu ingin mencoba untuk memperoleh yang lebih baik lagi dari apa yang sudah berhasil dia miliki. Sesuatu yang lebih hebat, lebih spektakuler dan itu semua juga bersifat sementara dan terus berakumulatif. Semua kenikmatan sesaat itu bukanlah kebahagiaan. Lalu seperti apa kebahagiaan yang lebih awet itu? Coba lihat kisah berikut ini.
Suatu hari Ali bin Abu Thalib berkata pada seorang laki-laki dari Bani Sa’ad.
“Maukah kamu saya ceritakan tentang saya dan Fathimah? Ia tinggal bersama saya dan ia adalah keluarga Rasulullah yang paling dicintai oleh beliau. Namun, ia mengambil air dengan qirbah (tempat air), sehingga menimbulkan bekas di dadanya; ia menggiling dengan gilingan, sehingga tangannya bengkak; ia membersihkan rumah, sehingga pakaiannya kotor; ia bahkan juga menyalakan api di bawah periuk. Ia betul-betul capai dengan pekerjaan itu. Aku pun mengatakan kepadanya, “Jika kamu menemui ayahmu, mintalah kepada beliau seorang pembantu, agar kamu tidak lagi kecapaian dengan pekerjaan ini.”
Fathimah pun pergi menemui Nabi saw. Di tempat nabi, ia mendapati banyak orang sedang bercakap-cakap. Ia merasa malu, lalu pulang.
Nabi tahu bahwa Fathimah datang karena ada keperluan. Beliau pun datang ke tempat kami. Saat itu, kami sedang berada di tempat tidur. Beliau mengucapkan salam, “Assalamu’alaikum.” “Wa’alaikumsalam. Masuklah, wahai Rasulullah.” Kataku. Masih dalam keadaan berdiri, beliau bertanya, “Wahai Fathimah, ada perlu apa kamu kemarin?”
Aku takut jika Fathimah tidak menjawabnya, beliau akan pergi. Aku pun mengatakan kepada beliau, “Saya ingin memberitahumu, wahai Rasulullah, bahwa Fathimah selalu mengambil air sehingga menimbulkan bekas di dadanya, suka menggiling sehingga bengkak tangannya, suka membersihkan rumah sampai berdebu pakaiannya dan suka menyalakan api di bawah periuk sampai kotor pakaiannya. Aku lalu mengatakan kepadanya, jika kamu datang ke tempat ayahmu, mintalah seorang pelayan kepadanya agar kamu tidak lagi kecapaian.”Beliau mengatakan, ‘Maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik bagi kalian dibanding seorang pelayan? Jika kalian hendak tidur, bertasbihlah 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali. Semuanya berjumlah seratus dalam ucapan, dan seribu kebaikan dalam timbangan.’ Fathimah mengatakan, ‘Aku senang dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya.’”(dikutip dari buku, “Fathimah Azzahra, penerbit Lentera Jakarta). Maka Ali berkata kepada Fathimah, “Kamu semula menginginkan dunia dari Rasulullah, kemudian Allah memberi kita pahala akhirat.”
Jadi, ujung pencarian kata bahagia itu adalah ikhlas; ikhlas karena dan hanya untuk Allah semata. Artinya untuk bisa merasakan bahagia itu maka orientasi akhiratlah yang harus kita tanamkan dalam kepala dan benak kita. Kenapa? Karena dunia dan segala sesuatu yang ada di atasnya tidak ada yang bersifat abadi.
Subhanallah (Maha Suci Allah); Alhamdulillah (Segala puji bagi Allah yang memelihara seisi alam); Allahu Akbar (Allah Maha Besar). Itu yang diajarkan oleh Rasulullah pada Fathimah dan Ali untuk mengurangi penderitaan mereka dan sekaligus untuk memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Bukan harta, budak atau materi dunia. Ketiga konsep ini, mengajak kita untuk senantiasa berprasangka baik pada apapun yang Allah berikan pada kita; juga mengajak kita untuk selalu bersyukur dan ikhlas. Segala sesuatu itu akan terasa memiliki nilai yang berharga jika hati kita dipenuhi rasa syukur atasnya. Segala sesuatu itu akan terasa ringan dan nikmat jika kita menerima dan melakukannya dengan penuh ikhlas. Jika semuanya ‘fine-fine saja’, ‘ikhlas-ikhlas saja’, maka rasa bahagia itu akan bisa kita rasakan di dalam diri. Itu sebabnya kebahagiaan itu hanya bisa dirasakan di hati individu yang bersangkutan saja. Tapi, bagaimana menjabarkan ini semua pada teman saya itu jika saya sendiri masih belajar untuk menjadi seorang yang bisa selalu brsyukur dan ikhlas? Paling banter teman saya itu akan mengatakan bahwa jawaban saya adalah jawaban klise. Hmm… klise memang; namun demikianlah.
Semoga Allah memberikan rahmatNya pada kita semua, dan saya doakan agar kamu dan saya serta ummat Islam di muka bumi akan memperoleh kebahagiaan sebagai hadiah terindah dari-Nya. Aamiin.
Oleh Ikhwan








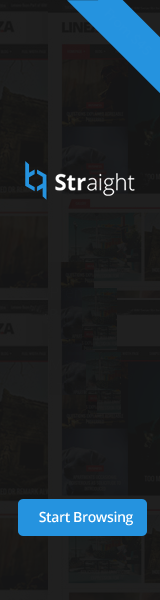



































No comments:
Post a Comment